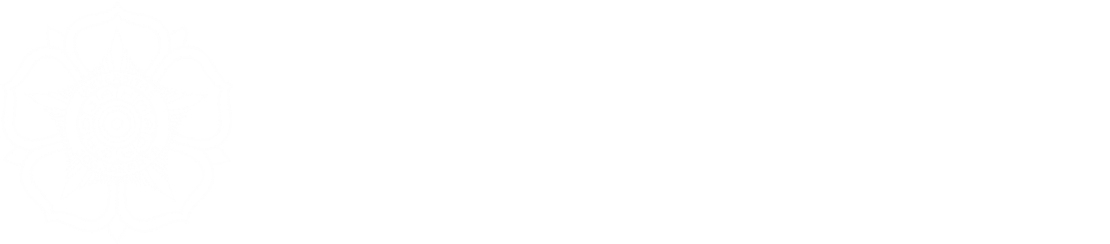Pemerintah kerap menyebut jumlah dokter Indonesia sudah mencukupi. Namun angka itu runtuh begitu ditarik ke peta persebaran dokter gigi khususnya di Indonesia. Di luar kota besar, rumah sakit masih kekurangan dokter spesialis. Puskesmas di wilayah perbatasan bahkan kosong berbulan-bulan. Masalahnya bukan pada kuantitas SDM dokter yang dihasilkan, melainkan distribusi dan dibalik kebijakan pendidikan kedokteran yang tak pernah benar-benar dirancang untuk infrastruktur kesehatan di daerah.
Forum akademik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) serta Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Gadjah Mada membuka kembali pertanyaan lama: ‘mengapa lulusan dokter spesialis tak kembali ke daerah asalnya, padahal disekolahkan dengan uang publik?’
Pesona Perkotaan Memang Memikat, Daerah Ditinggalkan..
Pola konsentrasi dokter spesialis di sekitar pusat pendidikan terjadi hampir tanpa pengecualian. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ratusan dokter spesialis terkumpul di Kota Yogyakarta dan Sleman. Kabupaten di sekitarnya hanya memiliki satu atau dua tenaga sejenis. Di Papua dan Kalimantan, ceritanya lebih ekstrem: layanan bedah, anestesi, hingga kedokteran gigi spesialistik sering kali tak tersedia sama sekali.
“Jumlahnya ada, tapi menumpuk,” papar Dr. dr. Sudadi, SpAn, KNA, KAR. dosen konsultan anestesi FKKMK UGM. Dari sekitar 4.000 dokter anestesi di Indonesia, lebih dari seperempatnya berada di Jakarta. Di luar Jawa, distribusinya semakin menipis.
Kondisi ini bukan kebetulan. “Dokter cenderung menetap di sekitar kampus karena jejaring profesional, fasilitas, dan peluang ekonomi tersedia di sana. Sistem pendidikan ikut memperkuat arus ulusan belajar di kota, bekerja di kota, dan jarang sekali kembali”, lugasnya.
Afirmasi Pendidikan: Solusi atau Jalan Pintas?
UGM mengembangkan program afirmasi pendidikan dokter spesialis, yang memberi jalur khusus bagi dokter dari daerah tertinggal. Pemerintah daerah membiayai pendidikan, universitas menyediakan penguatan akademik pra-seleksi, dan peserta menandatangani ikatan dinas untuk kembali.
Di atas kertas, skema ini menjanjikan. Namun implementasinya memperlihatkan lapisan persoalan lain.
Pertama, ketergantungan pada politik lokal. Beberapa peserta hampir putus studi karena kepala daerah berganti dan anggaran dihentikan. “Begitu gubernurnya ganti, program dianggap bukan prioritas,” ujar seorang pengelola program. Tanpa kontrak lintas periode, afirmasi mudah tumbang oleh siklus elektoral.
Kedua, beban akademik dan adaptasi. Peserta afirmasi tetap harus lulus seleksi nasional. Universitas menegaskan tak ada penurunan standar. Namun di balik itu, dosen mengakui proses pendampingan “harus digendong”—istilah internal untuk menggambarkan usaha ekstra membimbing peserta yang lama bekerja di daerah dengan akses ilmu terbatas.

Deployment Residen: Celah Regulasi atau Inovasi?
Langkah paling kontroversial adalah penempatan residen kelas mandiri di rumah sakit daerah yang belum memiliki dokter spesialis tetap. Dengan izin praktik nasional dan supervisi jarak jauh, residen menjalankan layanan sekaligus belajar.
Bagi daerah, ini solusi cepat. Layanan berjalan, rumah sakit hidup. Bagi universitas, ini memperluas jejaring dan daya tawar kerja sama. Namun skema ini juga menimbulkan pertanyaan: apakah negara sedang menormalisasi layanan spesialistik tanpa spesialis penuh?
Pengelola program menolak anggapan itu. Menurut mereka, ini transisi sementara hingga dokter lokal selesai dididik. Tapi tanpa pengawasan ketat, skema ini rawan menjadi substitusi permanen—residen datang dan pergi, sementara daerah tak kunjung mandiri.
Hilirisasi Tridarma dan Jejak Uang Publik
Isu lain yang mencuat adalah hilirisasi tridarma perguruan tinggi. Pengabdian masyarakat kini diarahkan ke model multieliks, melibatkan pemerintah, rumah sakit, dan sektor swasta. Contohnya, pelatihan penanganan hipotermia di kawasan wisata Dieng yang melibatkan dinas kesehatan dan pariwisata.
Namun di balik narasi kebermanfaatan, pertanyaan krusial muncul: siapa yang membiayai, dan siapa yang paling diuntungkan? Pengabdian menjadi sahih secara akademik karena menghasilkan publikasi dan policy brief, tetapi tetap bergantung pada konsistensi anggaran dan komitmen daerah.
Regulasi Lentur, Akuntabilitas Tertinggal
Diskusi lintas program studi membuka fakta lain: regulasi pendidikan dokter spesialis kini makin lentur. Rasio dosen-mahasiswa bisa ditopang jejaring, rekognisi pembelajaran lampau (RPL) memungkinkan pendirian program sebelum dosen lengkap, dan afirmasi dapat masuk jalur non-kuota.
Fleksibilitas ini mempercepat pemerataan. Tapi sekaligus memperbesar risiko: mutu pendidikan bergantung pada pengawasan, bukan lagi pada prasyarat ketat di awal.

Siapa Menjamin Daerah Tidak Sekadar Menjadi Laboratorium?
Pada akhirnya, afirmasi pendidikan dan deployment residen adalah respons terhadap krisis nyata. Tapi tanpa desain kebijakan yang tahan terhadap pergantian politik dan kepentingan institusional, daerah berisiko menjadi laboratorium kebijakan darurat, tempat uji coba, bukan tujuan akhir pemerataan.
Apakah negara sungguh ingin membangun sistem layanan kesehatan yang adil, atau sekadar menutupi kekosongan dengan solusi sementara yang tampak berhasil di atas kertas?
Reporter: Andri Wicaksono, Photographer: Fajar Budi Harsakti