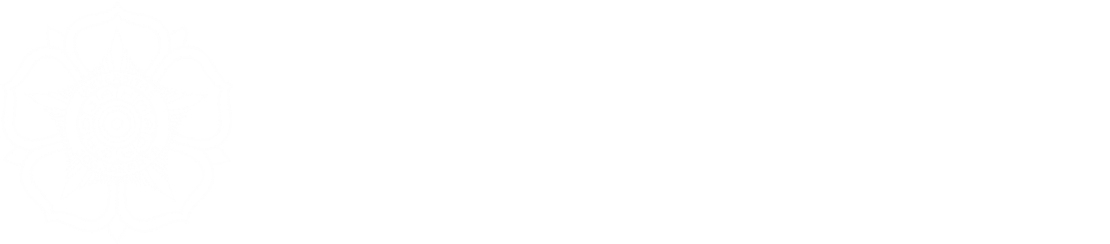Di balik jas putih dan senyum profesional dokter gigi, ada jam tidur yang terpotong, dompet yang menipis, serta mental yang diuji berulang kali. Kehidupan koas dan residen bukan sekadar fase akademik, melainkan perjalanan manusia belajar bertahan.
Di sebuah ruang rekaman sederhana, tiga generasi calon dokter gigi duduk berdampingan. Seorang mahasiswa profesi (koas), dua dokter residen spesialis, dan seorang moderator muda membuka percakapan tentang satu hal yang jarang dibicarakan secara terbuka: realitas hidup di balik pendidikan klinik kedokteran gigi.
Diskusi yang terekam dalam podcast kolaborasi HMPKG–GAMAPRO–BEM KM FKG Universitas Gadjah Mada itu menghadirkan drg. Mohammad Fadyl Yunizar, M.PH., Ph.D, residen Prostodonsia sekaligus dosen; drg. Hirzi residen Bedah Mulut dengan latar belakang dokter PNS daerah; serta Arya, mahasiswa profesi yang sedang menjalani koas. Dari ruang inilah, cerita-cerita tentang lelah, pengorbanan, dan keteguhan mental mengalir apa adanya.
KOAS: SEKOLAH MENTAL, BUKAN SEKADAR NILAI
Bagi Arya, fase koas adalah titik balik dari kehidupan mahasiswa. Jika di preklinik mahasiswa sibuk mengejar nilai dan teori, di koas ukuran keberhasilan berubah drastis.
“Pintar itu bukan nomor satu. Mental yang paling utama,” ujarnya.
Koas menuntut mahasiswa mencari pasien sendiri, mengatur jadwal sendiri, bahkan menanggung biaya sosial dan emosional yang tak tertulis di silabus. Tidak jarang, mahasiswa harus menjemput pasien dari daerah pinggiran, membiayai makan mereka, hingga mengorbankan waktu pribadi demi satu tindakan klinis.
Dalam sistem pendidikan berbasis requirements, satu hari tanpa pasien berarti satu hari lebih jauh dari kelulusan. “Menunda satu hari, artinya menunda kelulusan,” kata Hirzi, yang pernah merasakan langsung fase ini sebelum masuk residensi.
RESIDEN: KETIKA HIDUP TIDAK LAGI MILIK SENDIRI
Jika koas adalah ujian ketahanan mental, residensi adalah ujian ketahanan hidup. Hirzi, yang sebelumnya bertugas sebagai dokter gigi PNS di daerah Kalimantan Selatan, menggambarkan fase ini sebagai masa paling berat.
Pendapatan berhenti, tanggung jawab keluarga meningkat, sementara beban akademik dan klinis justru berlipat. Beasiswa memang ada, tetapi tekanan psikologis tidak bisa sepenuhnya dibantu oleh dana.
“Kalau dulu minta uang ke orang tua, sekarang istri yang minta uang. Tapi kita tidak punya,” tuturnya.
Sementara itu, Fadil menjalani residensi bersamaan dengan perannya sebagai dosen dan pejabat struktural fakultas. Waktu menjadi barang langka. Tidur sering dikorbankan, tugas dikerjakan dini hari, dan akhir pekan jarang benar-benar menjadi waktu istirahat.
Namun, ada satu benang merah yang mereka pegang: menunda kesenangan.
“Kami hanya menunda kesenangan. Kurikulumnya lima tahun. Lama sekali. Tapi hasilnya sepadan,” ujar Hirzi
MENJADI SPESIALIS: ILMU YANG DIULANG RATUSAN KALI
Perbedaan paling nyata antara koas dan residen terletak pada fokus keilmuan. Koas dituntut memahami kedokteran gigi secara menyeluruh. Residen, sebaliknya, masuk ke lorong sempit yang dalam.
“Kalau koas mencabut gigi 20 kali, kami bisa 500 kali,” kata Hirzi. Pengulangan itulah yang membentuk keahlian spesialistik—sebuah kompetensi yang tidak bisa diperoleh dari video daring atau pengalaman singkat.
Fadil menambahkan, pengalaman klinis harus berjalan seiring dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based). Tanpa landasan ilmiah, praktik klinis berisiko menjadi sekadar kebiasaan yang tak teruji.
Di akhir percakapan, para narasumber sepakat bahwa pendidikan dokter gigi bukan sekadar soal keahlian medis. Ia adalah pendidikan karakter.
Tentang kegagalan yang tak terhindarkan. Tentang bangkit setelah ditolak dosen. Tentang mencari teman seperjuangan yang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Tentang tidak melupakan kewajiban spiritual di tengah kesibukan duniawi.
“Garis finis itu ada. Belum waktunya berhenti,” kata Arya menutup perbincangan.
Di ruang podcast itu, tidak ada glorifikasi. Yang ada hanyalah kejujuran. Bahwa menjadi dokter gigi, terutama spesialis adalah perjalanan panjang yang sunyi, tetapi bermakna. Perjalanan manusia biasa yang belajar sabar, sebelum akhirnya dipercaya merawat manusia lain.
(Reporter: Andri Wicaksono, Foto: tangkapan layer Youtube Podcast Cerita Kage